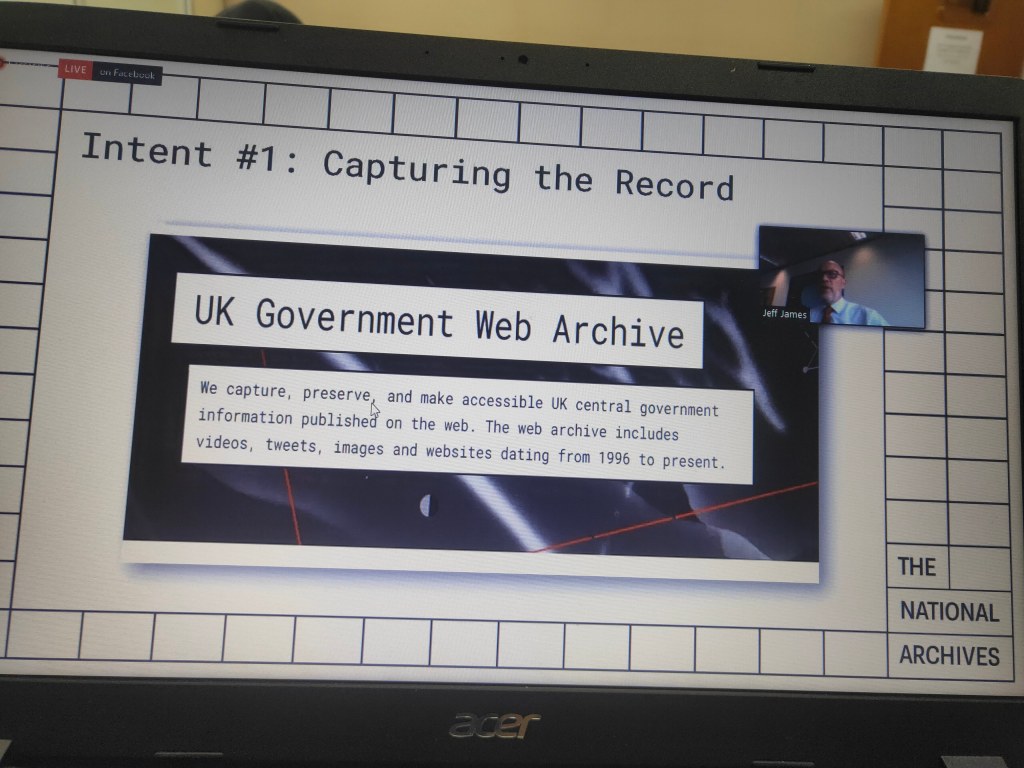Saya termasuk orang yang malas eksplorasi musik baru, referensinya seperti mentok di situ-situ saja. Agar bisa benar-benar “masuk” dengan musik baru, terkadang perlu momen-momen tepat ketika pengalaman itu datang dan dilanjutkan ngulik entah itu lirik maupun sosok personilnya. Beberapa band atau musisi yang saya gemari saya dapat dari proses itu. Selain Bon Iver dan Phoebe Bridgers, The Trees and The Wild (TTATW) adalah salah satu band yang ada ruang tersendiri di hati saya.
Saya pernah menuangkan apa yang saya rasakan dan saya alami terhadap TTATW dalam sebuah tulisan yang begitu mentah dan naif. Nggak usah repot-repot dibaca tapi, ya. Malunya minta ampun. Cringe alert. Namanya juga bocah baru kenal iNdiE. Memang sengaja tidak dihapus karena saya anggap artefak dan pengingat bagaimana saya berkembang–walaupun faktanya masih sama begini-begini aja.
Tulisan ini merupakan respon lanjutan dari tulisan saya sebelumnya.
—-
Periode SMA (2010-2011) adalah puncak saya menikmati live pertunjukan TTATW dengan dua kali kesempatan menonton langsung. Pertama, di acara clothing di JEC Jogja akhir 2010, di mana pertama kali dibuat takjub mendengar lagu yang konon berjudul “Radoslav”. Entah bagaimana nasib lagu itu karena tak dimasukkan di track list album Zaman, Zaman. Padahal jika penasaran musik TTATW dan Barasuara dikawinkan, “Radoslav” ini prototipenya. Kesempatan kedua, pada pagelaran Smada English Night, pertengahan 2011. Momen itu masih sangat membekas, saya duduk di kelas 10 SMA dan pada malam yang sama dengan event TTATW ini, kelas saya sedang menggelar pementasan teater dan saya turut ambil peran, dengan egoisnya saya meninggalkan teman sekelas selepas pementasan usai hahaha.

(The Trees and The Wild di Smada English Night, Yogyakarta, 2011).
Pada saat itu, itulah kali terakhir saya menyaksikan mereka. Di tahun 2012 (atau 2013?), saya melihat kejanggalan ketika sadar Iga Massardi mulai jarang mengisi pertunjukan-pertunjukan TTATW. Puncaknya adalah tur Eropa di Estonia dan Finlandia yang menegaskan kemisteriusan keluarnya Iga. Tak pernah ada pernyataan resmi–itu sebab banyak isu yang mewangi di sana-sini. Pada saat yang sama, TTATW meresmikan tambahan tiga anggota: Tyo, Tamy, dan Innu. Waktu berjalan, lambat laun band ini lekat dengan label band mitos–antara ada dan tiada. Live gig makin jarang mengisi, sosial media pun sepi aktivasi.
Meski terkesan seperti hidup segan mati pun tak mau, di tahun 2016 TTATW mementahkan mitos itu dengan merilis album baru: Zaman, Zaman. Buah penantian panjang pendengarnya hadir juga. Perbandingan Zaman, Zaman dengan Rasuk tak bisa dihindari mengingat pivot yang dilakukan TTATW cukup radikal. TTATW seperti sengaja ingin melepas label folk yang kadung tersemat di mereka sejak album Rasuk mencuat. Konsep baru diusung. Seluruh track di album Zaman, Zaman sepenuhnya menggunakan lirik Bahasa Indonesia, komposisi yang penuh repetisi dan noise ambience yang riuh di mayoritas track.

(Showcase The Trees and The Wild di Rossi Musik, Agustus 2019.)
Waktu berjalan, delapan tahun berlalu sejak terakhir saya menonton mereka, tidak terbersit kesempatan menontonnya kembali akan hadir. Tak disangka, Sabtu, 31 Agustus 2019, TTATW menggelar showcase tunggal sekaligus merayakan sedekade album Rasuk. Tentu, nomor-nomor dari album Zaman, Zaman mendominasi set list, dengan disisipi beberapa lagu dari album Rasuk yang masih relevan dengan konsep baru TTATW.
Jika digambarkan, menyaksikan TTATW formasi baru itu bagai ritual penyembahan sekte: terbius dan terperangah dalam kagum. Penempatan komposisi disusun taktis. Bunyi-bunyi dieksplorasi secara teliti. Set panggung dipugar hingga tampak segar. Latar visual dikonsep dengan serius yang tampak dari pergantian satu lagu ke lagu lainnya dibarengi dengan pergantian latar visual–apapun itu, saya tetap menikmati suguhan langka ini.
Di tengah menikmati pertunjukan itu, saya sadar satu hal. Makin saya tenggelam dalam Zaman, Zaman, makin saya memahami Rasuk memiliki arti lain. Rasuk tidak selalu berada di nomor teratas dalam playlist saya dan tidak pula menjadi pilihan go-to saya ketika memilih lagu untuk “niat” didengarkan. Ketika mendengarkan Rasuk, ia seperti kawan karib lama yang jarang bertegur sapa, dan ketika sesekali saling bertukar kabar ada perasaan hangat di dada dan memori-memori kolektif yang bersama dilalui menyeruak kembali. Sedangkan Zaman, Zaman adalah versi murky old man yang ultra serius, sibuk dengan dirinya sendiri dan persetan dengan sekitarnya.
Di Zaman, Zaman ini, saya tidak lagi menemui perasaan sekhusyuk mendengar “Kata”. Tidak lagi menemui perasaan dikejut keseruan progresi “Derau dan Kesalahan”. Tidak lagi menemui perasaan merayakan keraguan masa depan dengan naif seperti di “Fight The Future”–semua terasa sederhana dan mengena di umur dan momen-momen penting kala itu.
Zaman, Zaman tidak (atau belum?) memberikan pengaruh sebesar itu. Mungkin penilaian saya terlalu prematur. Mungkin juga selera saya yang terlalu pop.
Atau mungkin, saya masih saja terbuai ribuan sangkalan untuk mengakui bahwa saya sudah menua dan enggan merelakan masa-masa ketika tumbuh bersama album Rasuk sudah jauh berlalu, dan menerima bahwa Zaman, Zaman–seperti halnya proses di diri saya–adalah proses pendewasaan yang niscaya.